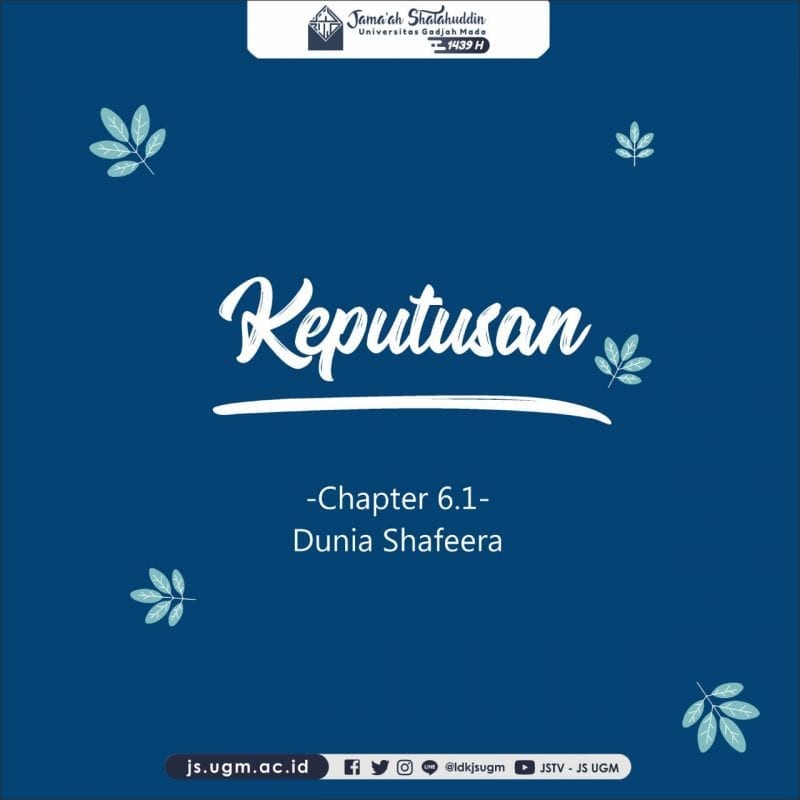
Jarum jam di ruang tamu menunjukkan pukul empat sore. Hawa di kala itu sama sekali tidak tertebak, tetapi di sinilah kuharap segalanya dapat terurai dengan sebaik-baiknya. Kami saling sambut-menyambut, bersalam-salaman, bercium pipi. Memberikan senyum terbaik, simbolisasi dari suatu diplomasi. Semua pun duduk pada posisinya masing-masing, tertata rapi, seakan segalanya telah terencana sejak sehari sebelumnya. Padahal, tidak siapapun dari kami mengetahui hal-hal yang kelak akan terjadi.
Setelah cangkir-cangkir yang semula penuh dengan teh panas itu pelan-pelan meninggalkan setengah dari bagiannya—atau bahkan habis sama sekali—ketegangan terasa menebal di antara jarak tubuh-tubuh kami. “Jadi…” ayahku membuka suaranya, “saya dengar dari nak Shafeera bahwa masnya hendak menikah lagi. Apakah itu betul, nak?” Pertanyaan itu ia lontarkan kepada suamiku. Terlihat dengan jelas bahwa ia sama sekali tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut, tetapi kendati demikian, ia mengiyakannya. Keheningan sejenak memenuhi ruangan setelah jawaban itu ia berikan, sesuatu yang entah mengapa mendorong hati nuraniku untuk segera mencari momentum yang tepat. Saat untuk melakukan penyibakan yang seharusnya kulakukan sejak awal, yang semestinya dapat menyelamatkanku dari berbagai luka.
“Maaf,” ucapku. Walaupun sebenarnya dalam konteks ini, akukah yang sepatutnya meminta maaf? “Maaf… Shafeera meminta maaf. Kepada kedua orang tua dan mertua Shafeera yang amat Shaf hormati dan sayangi. Kepada suami Shaf. Maaf…
Ibu, Ayah, Mas, serta Ibu dan Ayah Mas—maafkan Shafeera. Sebenarnya, Shaf tidak pernah setuju untuk menikah dengan Mas. Namun, di saat pernikahan kita dicanangkan, Shaf rasa… Shaf sama sekali tidak memiliki posisi untuk melakukan penolakan. Ibu dan Ayah kita berdua telah begitu yakin, bahwa Shaf-lah perempuan yang sepatutnya membahagiakan Mas, hanya karena Shaf adalah anak Ayah dan Ibu yang memiliki hubungan baik dengan orang tua Mas.
Dalam hal ini… Shaf rasa, kedua pihak orang tua kita sama sekali tidak melihat Shafeera sebagai seorang Shafeera. Shaf hanya dipandang sebagai suatu bentuk terima kasih atas segala jasa orang tua Mas kepada orang tua Shaf. Namun… tidakkah Shafeera lebih daripada sekadar itu? Bukankah Shaf pun seorang manusia yang berpikir dan merasa, serta berhak memilih untuk dirinya sendiri?
Ya… kini Shaf sadar, bahwa dari beribu cara untuk membalas kebaikan yang tak terhingga dari orang tua, menjalani pernikahan yang hanya merupakan kehendak orang tuamu bukanlah salah satunya. Oleh karena itu, sekali lagi, Shaf ingin meminta maaf… atas segala kepura-puraan yang Shaf lakukan dengan menyandiwarakan bahwa segalanya baik-baik saja, menutupi kenyataan yang sebenarnya: bahwa Shaf merasa begitu tersakiti. Shaf harap, semua itu bisa dimaklumi…”
Sembari pidato itu aku berikan, terdengar helaan napas berulang yang menandakan keresahan yang muncul di penjuru ruang tamu. Kemudian keheningan itu kembali, ia yang justru menikam ketenangan yang berada di dalam hati-hati kami—menyambut sebuah balasan yang berasal dari suamiku sendiri. “Saya juga hendak meminta maaf,” ucapnya, “sebenarnya sejak awal, saya pun ragu terhadap keputusan itu. Maafkan saya Ibu, Ayah; serta Ibu dan Ayah Shafeera—dengan penuh penyesalan, harus saya akui bahwa menurut saya, yang diucapkan Shafeera adalah benar. Shafeera tidak pernah dipandang sebagai dirinya dalam pernikahan ini, dan itulah yang dari awal membuat saya tidak pernah memandangnya demikian pula. Bagi saya, hingga hari ini, ia adalah hadiah dari orang tua saya yang sudah sepatutnya saya terima. Namun, ternyata… hadiah ini pun memiliki pandangan-pandangannya sendiri, dan seringkali pendapat kami berseberangan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat hubungan di antara kami menjadi sama sekali tidak baik. Dengan itu… saya rasa, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada baik orang tua Shafeera maupun Ayah-Ibu saya sendiri… saya rasa, sebaiknya pernikahan ini diakhiri saja.”
“Baiklah,” balas Ayah suamiku, “baiklah anakku, serta nak Shafeera… kami semua pun hendak meminta maaf. Maafkan kami yang barangkali terlalu cepat menilai bahwa pernikahan antara anak-anak kamilah yang sepatutnya dilakukan untuk kebaikan bersama, tanpa memperhitungkan dengan baik pendapat kalian berdua sebagai pihak yang menjalaninya. Jika memang inilah keputusan terbaik, maka sudah sepatutnya jalan inilah yang kita tempuh. Meskipun tidak ada yang menginginkan suatu perceraian untuk terjadi, tetapi marilah kita tempuh proses ini dengan sebaik-baiknya…”
Usaha-usaha untuk melakukan perceraian yang diakui oleh negara pun dijalankan. Ia yang waktu itu masih berstatus sebagai suamiku mengirimkan gugatan talak kepada Pengadilan Agama setempat; kemudian sidang demi sidang kami lalui sebagai sebuah pasangan. Aku sudah siap untuk melepas statusku sebagai istrinya, seorang perempuan yang sedari awal tidak pernah ia pilih, pun tidak pernah memilih untuk menikah dengannya. Selama proses itu berjalan, aku pun menangkap kesan yang sama dari lelaki itu. Sejak persidangan ini dimulai, sebenarnya aku telah memiliki perasaan yang kuat bahwa akhir dari persidangan ini telah jelas: ikrar talak dari pihak suami—dan pada akhirnya, memang hal itulah yang terjadi.
***
Namun, perceraian jelas bukanlah proses yang kekanak-kanakan. Sebuah ikatan sesuci pernikahan tidak berakhir dengan begitu saja, dengan hilangnya pasangan yang telah menyayat hatimu dalam sekejap mata dari relung kehidupanmu. Saat ini, aku sedang menjalani masa ‘iddah sebagai seorang istri yang baru saja ditalak suaminya. Proses ini aku jalani selama tiga kali menstruasi; aku belum resmi bercerai dari suamiku sebelum masa itu selesai. Sekarang, aku sedang berada di penghujung siklusku yang ketiga sejak talak diikrarkan di hadapan mereka yang hadir di persidangan pada hari itu, dengan kesadaran bahwa sebentar lagi, resmilah sudah bahwa aku bukan seorang istri lagi. Sebagaimana seharusnya, aku menjalani masa ‘iddah ini di kediaman yang sama, di tempat aku pertama kali sampai sebagai sepasang pengantin baru. Kurasa, hari-hariku saat aku menjadi seorang istri dan rutinitas yang kujalani hari ini di penghujung ‘iddah-ku sama saja—aku masih merasa seperti sebuah benda yang tidak signifikan.
Meskipun dalam waktu yang singkat lepaslah sudah ikatan itu, mengapa aku malah merasa takut terhadap hal-hal yang akan datang? Setelah resmi sudah bahwa aku bukanlah istri dari lelaki yang meninggalkan bekas-bekas yang menyakitkan dalam kehidupanku, lantas apa? Tidak ada seorangpun yang mengetahui masa depannya, bahkan seorang nabi sekalipun. Akan tetapi aku rasa, memang manusiawi bagi kita untuk tetap merasa takut terhadap misteri-misteri yang tersimpan di dalam masa depan kita, yang hanya bisa terungkap dengan berjalannya waktu. Sesaat setelah pikiran itu terlintas di dalam benakku, tanpa kusangka-sangka, telepon genggamku berbunyi—dan yang lebih tidak disangka lagi, panggilan tersebut masuk dari lelaki yang mentalakku.
Ini sangat tiba-tiba. Selama menjalani pernikahan dengannya, bisa kuhitung dengan sepuluh jemariku kali ia meneleponku. Karena tidak ingin memperpanjang perkara ataupun membuat situasi menjadi lebih rumit, aku pun mengangkat telepon itu; sambil berusaha untuk menjaga ketenangan diri serta melepas berbagai ekspektasi yang muncul di benakku. “Assalamu ‘alaykum Shafeera,” ujar suara yang familiar itu, “Wa ‘alaykumussalam,” jawabku, “Iya, Mas. Ada apa?”
“Begini, Shafeera,” ia berkata, “saya ingin bicara denganmu nanti malam. Ada sebuah restoran yang menjadi favorit saya serta ayah dan ibu saya; saya ingin berbicara denganmu di sana, sembari kita memakan hidangan favorit kita sekeluarga. Kamu siap-siap ya, insya Allah nanti saya jemput kamu setelah maghrib.” Mendengar pernyataan itu, aku semakin yakin bahwa masa depan memang merupakan sesuatu yang tidak pernah dapat kita terka. Siapa yang menyangka bahwa lelaki yang sama yang mentalakku sekitar tiga bulan yang lalu, kini mengajakku makan di restoran favoritnya dan keluarganya?
Sekali lagi, karena tidak ingin memperpanjang ataupun memperrumit, aku langsung mengiyakan ajakan tersebut. Aku pun melakukan hal yang ia minta, sebelum adzan maghrib berkumandang, aku berbersih diri dan mengenakan baju yang pantas untuk dipakai keluar rumah. Tepat jam 19.05, aku mendengar suara mobilnya yang mendekat, suara yang menjadi bagian dari keseharianku selama ini. Namun, hari ini rutinitas itu sungguh berbeda—aku tidak hanya akan menyambut kedatangannya; hari ini, aku pun dijemputnya dan pergi bersama dengannya.
Bersambung ke Part 6.2

